Tempat paling damai di Bumi
(Pengalaman pribadi menemukan komunitas damai)
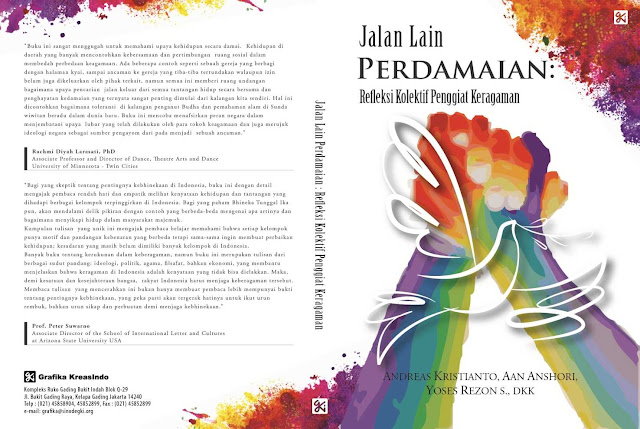 |
| Artikel ini adalah salah satu tulisan yang diterbitkan dalam buku ini |
Pengantar
Tulisan ini adalah
refleksi dari pengalam panjang penulis mencoba menemukan komunitas manusiawi
yang bisa dirasakan sebagai “rumah” dan tempat paling damai di bumi. Begitu
panjang dan pentingnya pengalaman itu bagi usaha kita bersama memahami hidup
damai dalam kepelbagaian dan bagaimana membangun sikap diri (personal maupun
organisasional) yang otentik penuh semangat menuju kedewasaan bersama dengan
orang-orang disekitar kita, maka detail peristiwa tidak diutamakan. Penulis
berusaha fokus pada perjumpaan-perjumpaan dengan realitas yang paling penting
yang memberi pelajaran, membuka wawasan dan mendewasakan penulis.
Pertanyaan paling penting
Dimanakah tempat paling
damai di Bumi? Apakah di rumah, ketika semakin hari semakin nampak bahwa bahkan
sistem pendidikan yang lazim dilakukan dalam keluarga cenderung abusif dan
mencetak generasi baru yang tidak mampu menentukan dengan bebas identitas
dirinya? Apakah di sekolah atau kampus, yang semakin populer dimaklumi bahwa
semakin kritis dan progresif seorang siswa atau mahasiswa, semakin kesulitan
dia mendapatkan akses terhadap kelangsungan pendidikannya? Apakah dalam lembaga
keagamaan, yang semakin hari semakin memperlihatkan bahwa kesibukan utamanya
bukan lagi membangun keutuhan kemanusiaan yang bergaul dengan Tuhan, namun
birokrasi ekonomi politik, tata organisasi, dan ambisi mengedepankan
simbol-simbol duniawi sebagai keberhasilannya? Pertanyaan-pertanyaan besar
seperti ini selalu mengganggu nalar sehat siapapun yang dengan ketulusan
membuka diri, menjadi diri sendiri, dan yang selalu berusaha mencari
jalan-jalan damai.
Pertanyaan-pertanyaan
di atas akan semakin panjang dan mengganggu ketika seseorang memiliki masa lalu
yang tidak menyenangkan beberapa orang, yang mengecewakan lembaga moral, dan
yang membuat marah pemakluman sosial karena tabu yang dijunjung terlalu tinggi
terbongkar kebusukannya. Demikianlah pengalaman saya menelusuri jalan-jalan hidup
otentik apa adanya mencoba menemukan tempat paling damai di Bumi. Sebagaimana
semua orang berusaha mencarinya, pencarian itu aku mulai dari diriku sendiri.
Untuk itu pertanyaan
pertama yang aku tegaskan pada diriku sendiri adalah menyadari sepenuhnya
bagaimana cara pandang diriku memetakan, merasakan, menggambarkan, menamai, dan
hidup di dalamnya. Jelas orang yang mencari tempat paling damai di dunia
bukanlah orang yang sempurna. Karena ternyata tempat paling damai di dnuia itu
bermula dalam pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, yang memilih
jalan-jalan damai dengan segala macam resikonya, dan tetap menghidupi damai
sepanjang jalan itu.
Tempat paling aman
Tidak ada seorangpun
yang bisa memastikan sebuah tempat adalah tempat paling aman di dunia ini.
Karena tempat paling aman adalah tempat dimana seseorang merasa paling bebas
menjadi dirinya sendiri, tempat dimana keunikan-kekurangan-kelebihan dihargai
sebagai peluang belajar menjadi semakin dewasa, sebuah tempat dimana
orang-orang yang ada disekeliling kita adalah orang-orang yang sepenuhnya bisa
dipercaya tidak akan berbuat jahat kepada kita apapun situasinya.
Sesungguhnya sederhana,
namun dalam konteks kultural dan psiko-sosial masyarakat yang khabarnya ramah
tamah dan penuh pengertian ini, menemukan tempat paling aman tidaklah mudah.
Dimanakah kita bisa menjadi diri sendiri dengan bebas jika harmoni dimaknai
dengan cenderung melihat pada persamaan-keseragaman-persetujuan-pemakluman,
keselarasan diakui jika terjadi ketundukan pada suara kebanyakan, dan
ketenangan ditekankan sebagai keadaan tanpa adanya ide-ide besar yang
menghasilkan perbedaan-perbedaan yang kontras?
Menemukan tempat paling
aman ternyata butuh kerja keras bernegosiasi, berkompromi, dan bahkan
mentoleransi banyak hal yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena setiap orang
akan berhadapan dengan paradoks realitas sosial. Tentu ada banyak aspek yang
bisa menolong seseorang untuk dapat berekspresi dengan merdeka dan menemukan
penghargaan yang semestinya. Namun ada banyak ketentuan, hukum komunal,
kebiasaan, adat, tradisi, aturan-aturan tak tertulis bahkan yang tertulis
dengan asumsi memiliki kesucian tertinggi, dan lain sebagainya yang tidak
selalu mampu menampung identitas diri, ekspresi terbaik, dan minat paling
menonjol seseorang.
Karena hal-hal itulah,
sering muncul persoalan mayoritas dipertentangkan dengan minoritas, persoalan
anggapan umum (common sense)
dipertentangkan dengan sikap pribadi, bahkan persoalan kekuasaan yang sering
dengan latah dan salah kaprah dijadikan rujukan terakhir menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi
dipertentangkan dengan kehendak rakyat. Maksudnya begini; karena perbedaan
antara seseorang dengan seorang yang lain itu kadang bisa sampai pada persoalan
siapa benar dan siapa salah, siapa menang dan siapa kalah, maka dibutuhkanlah
otoritas tertinggi yang menghakimi. Bentuknya bisa berupa surat, ketentuan,
legalitas, peraturan, kitab, orang penting dan hebat, sampai pada kekuasaan
negara dengan alat militernya. Jadi logika yang terbangun adalah bahwa dalam sebuah
masyarakat, ketika relasi interpersonal berada dalam perbedaan kritis, otoritas
tertingginya adalah penghakiman berdasarkan hukum.
Saking dominannya
kesadaran pada logika itu, maka setelah negara, beramai-ramailah
institusi-institusi yang ikut-ikutan mengurusi masyarakat, organisasi-organisasi
masa, dan bahkan perkumpulan-perkumpulan komunal dari Rukun Tetangga (RT)
hingga kelompok minat, hobi dan kelompok keagamaan dan keyakinanpun membangun
aturan dan kebiasaannya, bahkan hukumnya sendiri. Tentu hal seperti ini
diperlukan dalam banyak hal. Namun tidak dalam semua hal. Karena tetap perlu
untuk selalu dipertanyakan bentuk-bentuk praktisnya. Apakah dengan mekanisme
yang dilengkapi dengan ancaman hukuman seperti itu, individu dapat menemukan
tempat paling amannya?
Sebagai sebuah contoh.
Gereja adalah organisasi yang entah apapun interpretasi denominasionalnya
(berdasarkan aliran-aliran) – berbasis pada nilai-nilai yang diajarkan oleh
Yesus Kristus. Pada prakteknya, sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, logika
hukum seperti di atas juga menjadi acuan penting dalam mengatur dan mengelola
kelangsungan organisasi dan bahkan bentuk-bentuk relasi interpersonal para
anggotanya. Maka selain ritual-ritual, peraturan-peraturan dan bahkan
konsekuensi hukuman pun disediakan dalam organisasi ini. Beginilah setiap
organisasi, apalagi institusi (yang memiliki induk kitab hukum berdasar
konstitusi) biasanya membangun kesadaran eksistensialnya. Maka sekali lagi
pertanyaan diatas semakin menguat, apakah gereja masih merupakan tempat yang
aman bagi kebebasan ekspresi orang untuk bergumul dengan sesamanya dan bergaul
dengan Tuhannya?
Dalam beberapa kasus
yang membuat geram para pejabatnya, terutama jika hal itu berkaitan dengan tabu
terbesar yang disembunyikan ketat sebagai kesombongan identitas diri, gereja
terbukti tidak mampu lagi menjadi tempat yang aman. “Pelanggaran” terhadap
otoritas gereja sebagai pemegang tafsir formal tentang moralitas dan sistem
relasional – yang biasanya dengan perasaan tanpa dosa mendasari legitimasinya
pada kenyamanan umum – bisa jadi sangat mengancam dan membuat seseorang
kehilangan kenyamanan dan keamanan hidupnya. Kasus perceraian, mempraktekkan
ritual dari denominasi lain (seperti babtis ulang) dan tradisi budaya yang
dianggap “non gerejani”, dan apalagi mempertanyakan kode etik dan mekanisme
kelayakan para pemimpin gereja, masih banyak dijumpai berakhir dengan perasaan
tidak aman dan tidak nyaman pada berbagai pihak.
Godaan Kekuasaan
Setiap
kelompok-komunitas, organisasi, maupun institusi dalam bentuk yang
bermacam-macam selalu berada dalam godaan kekuasaan. Godaan untuk menjadi
berkuasa. Godaan untuk menguasai dan menunjukkan bahwa kekuasaannya itu
berpengaruh terhadap kehidupan orang. Godaan seperti inilah yang sering menjadi
alat permainan dalam membangun mekanisme pengelolaan hubungan interpersonal. Dan
ketika kekuasaan sudah menjadi mekanisme penentu bentuk-bentuk relasi
interpersonal dalam sebuah kelompok-komunitas atau organisasi-institusi maka
secara alamiah dibutuhkan sebuah sistem yang mengikat bersama. Sistem memang
diperlukan, tetapi sistem bukanlah hasil atau kebutuhan sebuah kekuasaan.
Sistem sebenarnya dibuat untuk melayani manusianya, para anggota kelompok atau
organisasi. Ketika sistem dianggap sebagai alat kekuasaan, maka seluhur dan
sesuci apapun sebuah komunitas dan organisasi, dia akan menghadapi kenyataan
penindasan pada orang-orangnya sendiri. Namun begitulah godaan kekuasaan.
Membuat orang mudah tidak sadar bahwa sistem yang dibangun dalam sebuah
komunitas atau organisasi sesungguhnya bisa dikatakan ada atau eksis jika
melayani manusianya.
Sebagai sebuah contoh.
Ketika orang bicara soal toleransi, yang sebenarnya berarti ambang batas yang
bisa diterima oleh seseorang atau sebuah kelompok, apakah yang terpikirkan?
Toleransi terlalu mudah diucapkan ketika orang menjumpai perbedaan. Bahkan
dengan semena-mena kadang diartikan sekedar sebagai penghibur diri bahwa
sekalipun berbeda (entah bagaimana) sebenarnya kita sebagai manusia selalu
harus menmukan kesamaan-kesamaan. Toleransi bahkan dianggap sebagai bentuk
penerimaan apa adanya, pun terhadap tindakan jahat anti kemanusiaan. Oleh
karenanya selalu dibutuhkan penjaga toleransi, penjaga damai, penjaga
perbedaan-perbedaan. Inilah logika yang terbangun dalam sebuah sistem komunal
yang berasal dari godaan kekuasaan. Ada pengandaian umum bahwa, toh pada
akhirnya ada kekuasaan tertentu (entah itu negara, atau Yang Illahi) yang akan
mengadili dan menghakimi keragaman itu serta menentukan aturan terbaik bagi
semua. Bukankah begitu logika yang melahirkan SKB pendirian rumah ibadat?
Pembentukan FKUB dan bahkan segala bentuk proyek politisasi agama yang telah
membuat negara dan institusi di bawahnya bukan lagi tempat aman bagi orang beragama?
Dengan demikian
nampaklah bahwa pengembaraan menemukan tempat paling aman itu mengalami
kesulitan – kalau tidak mengalami kegagalan – tepat ketika seseorang memasuki
sebuah komunitas atau organisasi tertentu. Maka timbul pertanyaan, adakah organisasi
alternatif yang melampaui kesadaran alamiah dibawah godaan kekuasaan seperti
itu? Disinilah pengalaman paling penting yang saya alami. Tentu sebagai seorang
pencari, ada kalanya tanda-tanda yang setidaknya menunjukkan harapan perlu
segera diselami dan dirasakan. Pengalaman paling berharga itu adalah ketika
menemukan para sahabat yang mengarusutamakan dialog dalam mengelola interaksi
interpersonalnya melampaui segala bentuk godaan kekuasaan, legalisasi, sistem
moral, apalagi dogmatisasi keagamaan.
Gusdurian
Sudah cukup lama saya
mengagumi Gus Dur (K.H. Abdurachman Wahid) dan sudah cukup banyak tulisan dan
pikiran beliau mempengaruhi cara pandang saya tentang agama, politik
kebangsaan, pluralisme, dan terutama penerimaan dan pembelaan pada orang atau
kelompok kecil lemah tak berdaya. Seorang model pemimpin agama yang sangat
susah dijumpai di Indonesia bahkan di dunia. Resiko demi resiko ditantangnya
dengan senyuman penuh humor memberi tanda bahwa apapun keadaannya, kebahagiaan
tiap orang itu penting dan memberi ruang untuk berkembang baik dalam pemikiran
baru maupun pada kesadaran baru. Jelas sebagai orang Kristen, saya tidak
mendapat keleluasaan ekstra untuk bisa mendengar dan berinteraksi langsung
dengan gagasan-gagasan keagamaan beliau. Tapi dari banyak refleksi keagamaan
yang disampaikannya nampak jelas bahwa beliau dalah figur yang konsisten dalam
membangun praksis hidupnya. Itulah sebabnya, nilai-nilai keutamaan hidup (values) beliaulah yang sangat kuat hidup
di dalam hati banyak orang di Indonesia, apapun agama mereka. Begitulah ketika
saya mendengar banyak kawan membicarakan tentang munculnya komunitas Gusdurian
yang berusaha secara praksis mentransformasikan nilai-nilai yang dihidupi oleh
Gus Dur dengan sukacita saya berusaha menjadi bagiannya.
Dengan latar belakang
pengalaman bahwa tidak semua komunitas atau organisasi sosial itu pasti
berbasis nilai, saya merasa perlu untuk mengadakan pemetaan dan penjajagan.
Namun karena yang namanya komunitas atau organisasi sosial itu yang terutama
dan terpenting adalah manusianya, maka dalam komunitas ini, pertama kali dan
yang terutama adalah saya berjumpa dengan beberapa kawan baru yang ternyata
juga memiliki impian dan harapan yang sama dengan saya. Yaitu menemukan tempat
paling damai di dunia diantara orang-orang yang mampu melampaui prejudice dan yang berani menghayati
hidup beragamanya melampaui asumsi-asumsi primitif pemecah belah dan penghancur
kemanusiaan. Beberapa kawan saya ketemukan, sesungguhnya merekalah yang
menemukan saya. Berdiskusi bersama dengan kakraban kehangatan tentang banyak
hal yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa kali terlibat dalam aksi-aksi
penyuaraan perdamaian dan kemanusiaan. Dan seringkali berefleksi bersama
bagaimana bertumbuh menjadi manusia seutuhnya.
Ketika perjumpaan itu
semakin intens berada dalam level
personal yang tidak lagi sekedar status kawan di media sosial atau sekedar sama-sama
tercatat dalam buku induk organisasi tertentu, maka refleksi yang tumbuh lebih
pada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang paling disyukuri dimiliki
oleh tiap-tiap pribadi daripada menyibukkan diri dengan pengukuhan identitas.
Saat itulah, tempat aman dapat mulai dibangun bersama. Tanpa tembok, tanpa
birokrasi, dan tanpa segala bentuk pemisahan sosial yang dilekatkan sebagai
identitas personal seperti jenis kelamin, agama, etnisitas, usia, asal daerah,
dan lain sebagainya. Tempat aman seperti ini perlu dikerjakan terus, karena
tidak pernah sekali jadi dan lalu merasa mapan. Dialog yang dibangun dilandasi
pada semangat penghargaan, penghormatan, dan kepercayaan adalah pondasi yang
paling kokoh untuk membangun tempat aman. Bahwa setiap anggota komunitas
kehadirannya adalah berharga dan penting bagi dirinya sendiri, bagi orang lain,
dan bagi dunia ini. Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi berdasarkan talenta
dan minat terbaik yang sudah dikaruniakan Tuhan padanya. Begitulah perjumpaan
menemukan makna sakralnya dan nilai-nilai keutamaan hidup menjadi tindakan yang
paling efektif.
Mungkin kita bertanya,
mengapa nilai-nilai yang bisa menciptakan ruang paling aman bagi kehidupan
bersama yang plural? Yang pertama dan sangat mendasar adalah kesadaran bahwa
sejak dari penghargaan kita pada diri sendiripun kita menjumpai pluralitas.
Menghargai diri otentik yang plural itulah yang akan memampukan seseorang untuk
berani melihat perbedaan yang ada pada diri orang lain. Demikian seterusnya,
hingga setiap anggota komunitas saling melihat bahwa keberbedaan itu adalah
anugerah yang perlu disyukuri. Dengan langkah awal ini, nilai-nilai personal
(yang bisa berasal dari agama, ilmu, ketrampilan, kepekaan, kepedulian,
perasaan, dan sebagainya) mendapatkan tempat untuk saling diekspresikan dengan
merdeka. Semakin nilai-nilai personal itu diwujudkan dengan keterbukaan dan
kejujuran, maka semakin pula sebuah komunitas dapat menghidupi dirinya. Semakin
komunitas terbangun dengan kekuatan keragaman nilai-nilai semakin dialog
menjadi intensif, dan semakin relasi interpersonal semakin kokoh.
Agama yang
masing-masing dipercaya oleh tiap-tiap anggota komunitas adalah roh yang akan
sangat berperan penting pada saat ia meneguhkan nilai-nilai keutamaan hidup
bersama. Dalam posisi seperti ini, agama dihayati, diyakini, dipercaya, dipelajari,
dan dipraktekkan secara nyata karena menjadi nafas hidup nilai-nilai kehidupan
bersama itu. Agama dan kepercayaan dengan demikian menemukan kembali
fitalitasnya bagi kelangsungan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Inilah
yang biasanya disebut sebagai dialog kehidupan, sebuah proses bertumbuh bersama
untuk menghargai berkah anugerah yang illahi dalam mewujudkan kehidupan yang
manusiawi. Dalam dialog kehidupan, agama memiliki peran penting dalam menyediakan
tempat aman bagi kemanusiaan melampaui segala bentuk dogmatisasi, sistem dan
struktur yang dimilikinya.
Tempat paling aman di Bumi
Inilah proses panjang
perjumpaanku dengan kawan-kawan yang kemudian secara bersama-sama menemukan
wadah bersama dalam organisasi berbasis nilai yang disebut Gusdurian. Merekalah
orang-orang penting dan amat berharga yang menemaniku, bahkan bisa disebut
berjalan bersama mengiringi aku, sebagai manusia yang tidak sempurna, untuk
menemukan tempat paling aman. Pada saat kami bersama-sama, entah disebuah
rumah, di warung kopi, di tengah demonstrasi, di tempat-tempat yang disucikan,
dimanapun, kami merasakan ada ruang aman untuk menjadi diri otentik. Dengan
terus mengingat bahwa peluang untuk menunjukkan nilai-nilai kehidupan itu dapat
terjadi setiap saat dan dalam tiap kesempatan, aku merasakan bahwa yang disebut
tempat paling damai di bumi adalah disini. Tepat diantara peristiwa perjumpaan
dengan penerimaan tulus terjadi, tepat ketika segala perbedaan dihargai dan
disyukuri sebagai roh yang menghidupi, dan tepat dimana kejujuran dialog
menjadi bahasa yang terus menerus membahagiakan.
Karena bagiku,
menjumpai Tuhan tidak lain adalah menjumpai segala ciptaanNya termasuk segala
anugerah terbaik yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk. Menghormati Tuhan dengan
demikian juga tak lain adalah menghargai dan menghormati segala ciptaanNya itu.
Begitulah tempat paling damai di bumi, bagiku.


Komentar